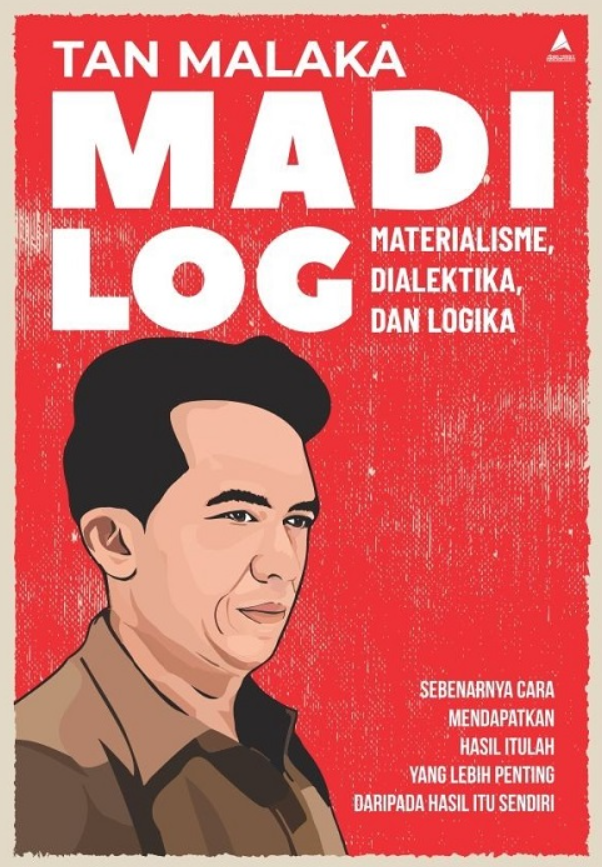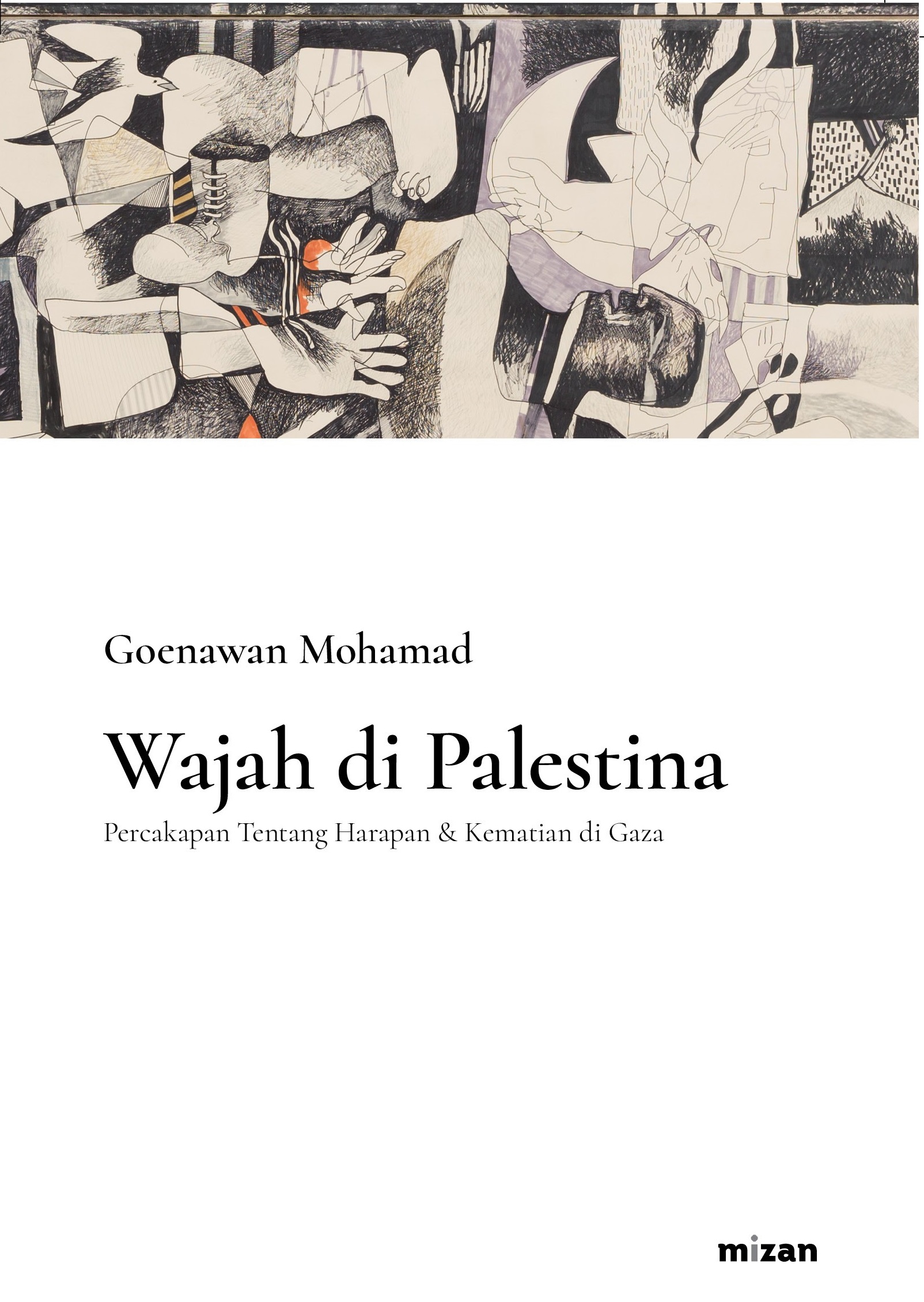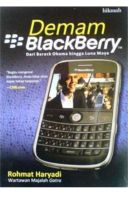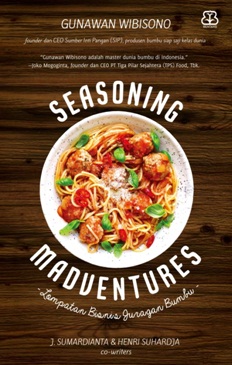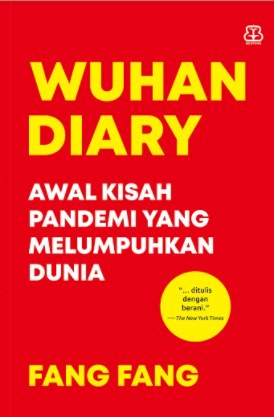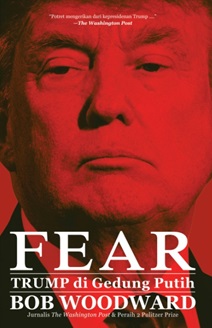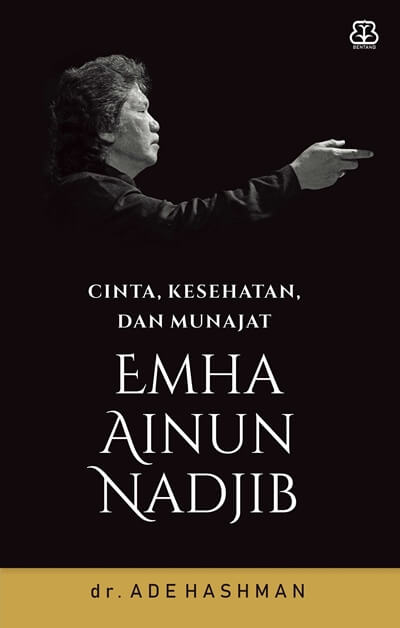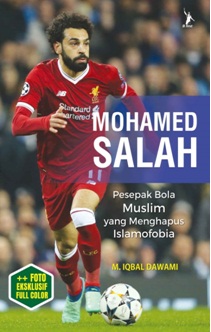Deskripsi
Menjelang usia satu abad, Indonesia semestinya sudah menjadi negara yang dewasa: dalam keberagamaan, rakyatnya saling menghormati; ekonominya maju; di dunia politik, para tokohnya menjadi negarawan; dan rakyat merasakan keadilan-sosial yang nyata.
Namun, kenyataan tidak demikian. Kedewasaan bangsa Indonesia hanya pernah terjadi pada masa lalu, tak lama setelah kemerdekaan. Waktu itu, Indonesia masih begitu muda, tetapi telah mencapai kedewasaan yang luar biasa. Rakyat Indonesia pernah mengalami dinamika kehidupan yang aman, damai, adil, dan jujur.
Buya Syafii Maarif, yang ketika menulis naskah-naskah ini sudah berada dalam usia senja, masih merasakan keresahan yang begitu kuat. Menurutnya, bukannya maju, Indonesia malah tampak berjalan mundur. Karenanya, ia mesti diselamatkan. Dalam buku ini, Buya mengupas persoalan-persoalan mendasar bangsa ini dengan jitu, bersumber dari kepekaan beliau. Tak berhenti sampai di situ, Buya menawarkan solusi-solusi yang tak kalah mendasar. Buku ini mengabadikan buah-buah pikiran beliau, melampaui masa hidup Almarhum.
PENGANTAR
OLEH: HAIDAR BAGIR
Kita semua pasti akan merasa berduka saat orang baik wafat. Dan itu adalah sebuah kewajaran. Tetapi, bagi orang-orang tertentu—sementara dia Insya Allah lebih bahagia di sisi-Nya—kepergiannya menyisakan duka yang lebih mendalam. Hal itulah yang saya rasakan ketika mendengar berita wafatnya Buya Ahmad Syafii Maarif. Bagi saya, bertemu beliau seperti bertemu dengan orangtua sendiri.
Pemikiran-pemikiran Buya Syafii, meski beliau kini sudah wafat, tak lekang oleh waktu. Semasa hidupnya, begitu banyak pemikirannya yang menjadi mata air bagi bangsa ini: kemanusiaan, toleransi, tenggang rasa, dan dukungannya terhadap kelompok minoritas di negeri ini.
Pancasila sebagai Civil Religion
Pemikiran Buya Syafii dapat dipastikan akan terus menjadi warisan yang sangat bermanfaat bagi perjalanan bangsa Indonesia hingga jauh ke depan. Pasalnya, sampai hari ini kita masih terus harus melihat kelompok-kelompok intoleran yang antiperbedaan di tengah bangsa kita. Kelompok jenis ini percaya terhadap suatu kebenaran, lalu memaksa yang lain agar menganut kepercayaan yang sama dengan mereka. Pada awalnya, mereka seperti berdakwah dan mengajak orang kepada keyakinan mereka secara sukarela. Namun, jika tidak mempan, mereka akan memaksa. Pada tingkat tertinggi, pemaksaan ini dapat mengambil bentuk kekerasan. (Perlu dicatat, kelompok intoleran bukan hanya ada di lingkungan pemeluk Islam, melainkan juga di agama lain.)
Meskipun digempur bertubi-tubi dengan begitu cepat dan masifnya oleh pergerakan kelompok intoleran seperti ini, untungnya bangsa kita masih memiliki alat yang dapat mengukuhkan keberagaman. Meminjam istilah sosiologi yang diperkenalkan oleh Robert N. Bellah, alat itu disebut civil religion (agama sipil). Civil religion bukan berarti agama baru, melainkan lebih merupakan wadah kesepakatan bersama di antara setiap warga negara. Civil religion adalah suatu bentuk kesadaran bahwa meskipun hidup dengan kelompok masyarakat yang berbeda-beda, kita dapat hidup berdampingan bersama dengan harmonis melalui sebuah kesepakatan yang dapat menampung kepentingan seluruh kelompok secara paling baik.
Konsep civil religion sesungguhnya bukan hal baru, sebab Islam sendiri pernah memperkenalkannya. Sewaktu Nabi Muhammad Saw. bersama keluarga dan para sahabatnya hijrah ke Yatsrib (yang belakangan bernama Madinah), beliau Saw. melihat bahwa wilayah oasis di tengah gurun ini dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, bersama perwakilan dari berbagai kelompok, Nabi merumuskan Piagam Madinah. Piagam tersebut terdiri atas 47 pasal, isinya menyangkut hukum perang, uang tebusan, jaminan keamanan, perdamaian, biaya, pengambilan keputusan, kebebasan beragama, dan banyak lagi. Pada kenyataannya, selain membahas hubungan antara sesama Muslim, hampir setengah dari Piagam Madinah membahas hak dan kewajiban orang-orang Yahudi. Salah satu poin terpenting dari piagam tersebut adalah bahwa setiap suku di Madinah terjamin keamanannya dan bebas untuk memeluk agama apa pun.
Dalam konteks Indonesia, jauh sebelum merdeka, bangsa ini memiliki civil religion, yang oleh Presiden Soekarno disebut “isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun, yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh budaya Barat”. Yang dimaksud oleh Soekarno tiada lain adalah nilai-nilai yang belakangan dirumuskan ke dalam Pancasila. Meski Pancasila baru diresmikan pada masa kemerdekaan, Soekarno yakin bahwa ia sudah ada dan mengendap selama berabad-abad di bumi Nusantara.
Saya percaya dengan konsep jiwa bangsa ini. Sebab, jauh sebelum masa kemerdekaan, Nusantara sudah dihuni oleh beragam kelompok masyarakat. Kita tahu bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali agama lama, di antaranya Kapitayan, Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan lainnya. Kenyataannya, kesemua agama lokal itu berpijak di atas prinsip kemanusiaan. Kemanusiaan itu sendiri adalah fitrah Allah Swt. yang ditanamkan ke dalam diri siapa pun, di mana pun, dan kapan pun, tak pernah berubah. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap manusia memiliki kecenderungan spiritual yang sama. Allah berfirman dalam Surah Al-Rûm, Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut) (QS Al-Rûm [30]: 30).
Setiap umat manusia mendapatkan wahyu dari Allah; yang membedakan adalah warna, corak, atau bentuknya ketika wahyu itu diterima oleh masing-masing kelompok. Ibarat prisma yang menerima satu sumber cahaya putih, kemudian memecahnya menjadi cahaya yang berwarna-warni. Perumpamaan lainnya adalah wahyu itu seperti air, bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ia tempati. Dalam filsafat Ibnu Arabi, konsep ini disebut dengan jibillah (disposisi). Allah berfirman, Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS Al-Baqarah [2]: 148).
Al-Qur’an juga mengatakan bahwa kepada setiap kaum selalu dikirim utusan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam hadis disebutkan bahwa jumlah nabi adalah 124.000 nabi. Jadi, tidak ada satu pun kaum—dengan masing-masing budayanya dan di pelosok mana pun—yang tidak diutus kepada mereka seorang rasul. Bisa diduga agama-agama lama di Indonesia, dan juga agama-agama besar yang sekarang kita kenal—Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan lebih banyak lagi—asalnya dari Tuhan yang sama.
Dan memang jika kita mau mempelajari, agama-agama asli Indonesia itu memiliki prinsip kepercayaan panteistik, alias Wahdahtul-Wujûd (ketunggalan wujud). Menurut prinsip ini, tak ada wujud di alam keberadaan kecuali wujud Allah—Lâ maujûda illal-Lâh—tanpa kehilangan prinsip pembedaan antara Khaliq dan makhluk. Wahdahtul-Wujûd melibatkan gagasan tentang sifat Allah yang musyabbah (imanen) dan munazzah (transenden) sekaligus. Begitu pula agama-agama lainnya. Secara spiritual, dan dalam bentuk aslinya, mereka adalah penganut Wahdahtul-Wujûd. Adapun jika ada penyimpangan pada agama-agama itu di kemudian hari, itu adalah soal lain. Jangankan agama lain, agama Islam yang kita yakini sebagai agama yang sempurna dan meluruskan agama-agama sebelumnya juga bisa mengalami penyimpangan oleh kesalahan penafsiran orang-orang Islam itu sendiri.
Saya percaya bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa sesungguhnya tidak hanya mencakup agama monoteisme, tetapi juga agama-agama lainnya, termasuk agama-agama lama Indonesia. Karena, memang sesungguhnya agama-agama tauhid, dalam konteks ini, lebih tepat disebut sebagai bersifat monorealistik (Wahdahtul-Wujûd).
Meskipun demikian, Pancasila bukan hanya dipengaruhi oleh jiwa bangsa Indonesia, melainkan juga oleh kebudayaan luar yang baik, mengingat kita tahu bahwa beberapa perumus Pancasila juga pernah mengalami pendidikan di Barat. Bahkan, bukannya tidak ada ahli yang menyebut bahwa Pancasila mendapat pengaruh dari Ajaran Sun Yat Sen. Ajaran ini dikenal dengan istilah San Min Chu 1 yang terdiri atas Min Tsen (kebangsaan atau nasionalisme), Min Chu (kerakyatan atau demokrasi), dan Min Sheng (kesejahteraan atau sosialisme). Bagaimanapun, saya percaya Pancasila adalah kandidat terbaik untuk civil religion di Indonesia.
Demikian pula, saya percaya agama dan keyakinan itu dalam satu hal bersifat relatif, tetapi tidak dalam makna seperti pendapat kaum relativis. Kita jelas yakin bahwa kebenaran mutlak itu satu, yakni yang berasal dari Allah Swt. Namun, ada banyak tafsir yang bisa jadi sebagiannya salah atau semuanya benar—hanya beda perspektif. Maka, konsekuensinya, harus ada toleransi atau penghargaan terhadap perbedaan, yakni mengakui kemungkinan kebenaran yang dipersepsi orang atau kelompok lain. Sebagaimana ada kemungkinan kebenaran dalam apa yang kita persepsi.
Pejuang Toleransi
Buya Syafii dalam salah satu pidatonya pernah bercerita, beliau dulunya anti-Pancasila. Hingga akhirnya beliau bertemu dengan Fazlur Rahman di Chicago, cendekiawan dan filsuf Muslim asal Pakistan, ketika sedang menempuh studi doktoral di Amerika Serikat. Setelah mendapat bimbingan dari Rahman, pikiran Buya menjadi terbuka. Beliau mengakui bahwa Pancasila begitu luar biasa, sumbangan terbesar dari para pendiri bangsa untuk Indonesia.
Buya juga—meskipun dengan istilah yang berbeda—menyetujui Pancasila sebagai civil religion. Meminjam istilah Nurcholish Madjid, Buya menyebut Pancasila sebagai kalimatun sawâ (prinsip/pegangan/proposisi dasar bersama) bagi Indonesia, baik untuk dahulu, sekarang, maupun masa depan. Istilah ini diambil dari Al-Qur’an Surah Âli ‘Imrân ayat 64.
Setelah mendapat pencerahan tersebut, sepanjang hidupnya, bahkan sejak menulis disertasi doktoralnya, beliau telah mencurahkan perhatiannya pada sejarah perumusan Pancasila. Belakangan disertasi beliau diterbitkan dengan judul Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante (Mizan, 2017). Kiranya ini adalah suatu upaya peletakan fondasi bagi pemahaman Pancasila secara utuh dan jernih. Selanjutnya, Buya selalu mempromosikan dan memperjuangkan nilai-nilai Pancasila beserta segala turunannya: toleransi, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan seterusnya. Menurut Buya, Pancasila bukan sekadar filosofi dan ideologi utopis yang hanya ada di alam pikiran belaka, melainkan bisa dan harus diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa secara konsisten, di semua aspeknya. Meski demikian, Buya juga mengakui bahwa cita-cita di dalam Pancasila belum sepenuhnya terwujud. “Ia [Pancasila] dimuliakan dalam kata, diagungkan dalam tulisan, dikhianati dalam perbuatan,” ujar Buya.
Buah keyakinan Buya terhadap Pancasila tertuang dalam begitu banyak tulisan. Tidak berhenti sampai di sana, dalam kesehariannya pun Buya mengimplementasikan Pancasila. Kehidupan dan kepribadian Buya adalah perwujudan Pancasila, sehingga beliau begitu dicintai oleh banyak orang dari semua golongan. Tidak peduli mereka dari kelas atas atau bawah, semuanya ingin berbicara dan meminta nasihat dari Buya. Maka, tidak berlebihan kiranya jika kita menyebut Buya sebagai Pancasila yang hidup.
Akhir kata, dengan penuh takzim kita sampaikan: selamat jalan, Buya. Selamat menikmati kemesraan bersama Yang Ilahi, yang Rahmat-Nya meliputi seluruh alam semesta. Meski kini Buya telah wafat, pemikirannya tetap abadi dan terus menyinari bangsa yang kita cintai ini. Sebagai wujud kecintaan kita kepada Buya, tiada cara lain selain kita terus merawat dan memuliakan berbagai warisan pemikiran beliau. Bi ‘auni-Hi Ta‘âlâ.[]
Spesifikasi
| SKU | : | UC-113 |
| ISBN | : | 9786024412944 |
| Berat | : | 400 gram |
| Dimensi (P/L/T) | : | 16 cm/ 24 cm/ 2 cm |
| Halaman | : | 356 |
| Tahun Terbit | : | 2022 |
| Jenis Cover | : | Soft Cover |
Ulasan
Belum ada ulasan