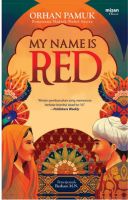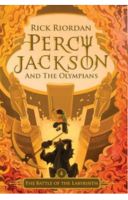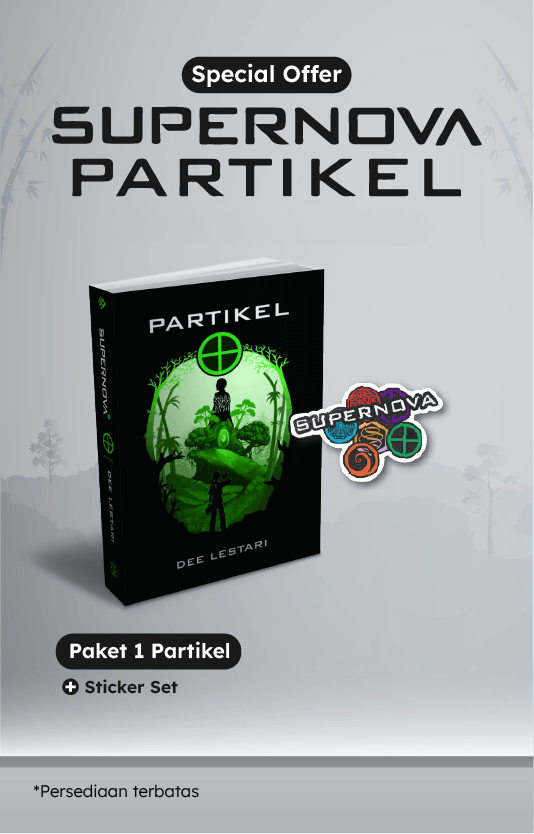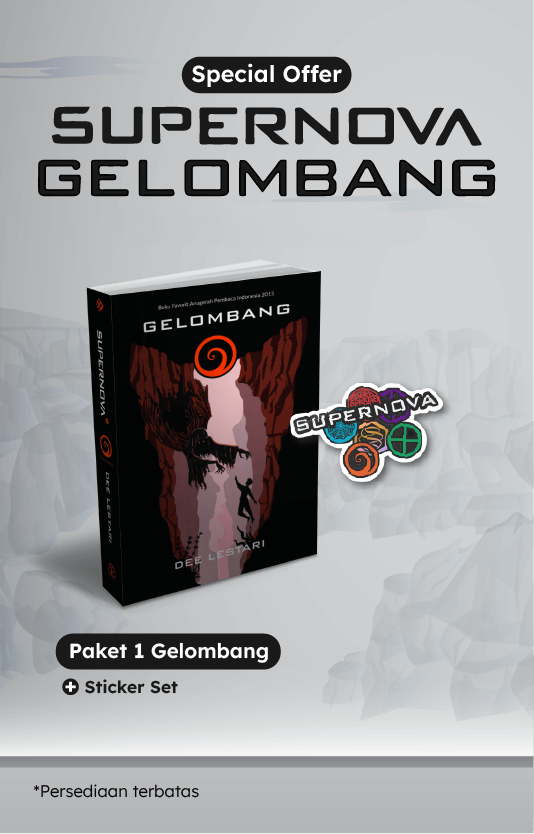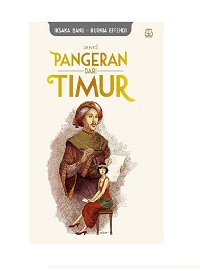
Deskripsi
Raden Saleh masih terlalu muda ketika dipisahkan dari keluarganya di Terbaya, Semarang, menjelang berakhirnya Perang Jawa. Kegeniusan dan tangan dinginnya dalam mengayunkan kuas tercium oleh para pejabat kolonial sehingga dia dikirim ribuan mil jauhnya menuju Belanda, sebuah negeri yang selama ini hanya didengarnya lewat cerita para kaum terpelajar Jawa. Terbukti dia mampu melukis bukan hanya sejarah dirinya yang gemerlap, melainkan juga wajah dan peristiwa zaman Romantis di Eropa. Bertahun hidup di tanah seberang, sang Pangeran justru merasa asing di tanah kelahirannya. Namun, tetap saja panggilan darah sebagai bangsa Jawa tidak dapat disembunyikannya di atas kanvas. Ditambah kegetiran yang menghiasi masa tua, karya dan hidup Raden Saleh berhasil menciptakan perdebatan sengit di kalangan kaum pemaham seni di masa pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia, satu abad berikutnya.
Syamsudin, seorang arsitek awal abad ke-20, menguasai pengetahuan seni yang berkembang pada masanya. Dia berhasil menularkan minatnya terhadap lukisan Raden Saleh kepada Ratna Juwita, gadis pujaannya. Di sisi yang berbeda, Syafei, dengan gairah pemberontaknya, menempuh jalan keras menuju cita-cita sebagai bangsa merdeka. Mereka melengkapi sejarah berdirinya sebuah negeri, dengan hasrat, ambisi, dan gelora masing-masing. Dan, di tengah kekalutan panjang sosial politik sebuah bangsa yang sedang memperjuangkan nasibnya, kisah cinta selalu memberikan nyala api: hangat dan berbahaya.
“Mereka dijauhi karena gagasan-gagasan pemikiran bebas mereka ... karena manusia yang berpikir merupakan objek menakutkan bagi orang Belanda, yang menuntut kepatuhan buta.”
— Therese von Lützow, sahabat Raden Saleh di Dresden
“Hormatilah Tuhan dan cintailah manusia.”
— Moto Raden Saleh yang tertulis di pintu masuk Masjid Biru di Maxen, Dresden
“Belajarlah dari Barat, tetapi jangan jadi peniru Barat. Namun, jadilah murid dari Timur yang cerdas.”
— Tan Malaka
Spesifikasi
| SKU | : | BT-563 |
| ISBN | : | 9786022916758 |
| Berat | : | 700 gram |
| Dimensi (P/L/T) | : | 16 cm/ 24 cm/ 4 cm |
| Halaman | : | 604 |
| Tahun Terbit | : | 2020 |
| Jenis Cover | : | Soft Cover |
Ulasan
Belum ada ulasan