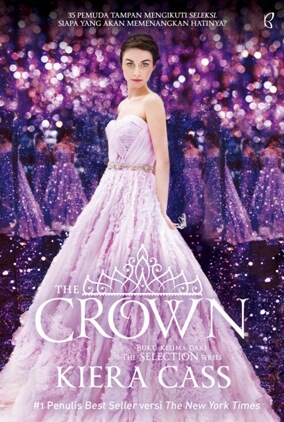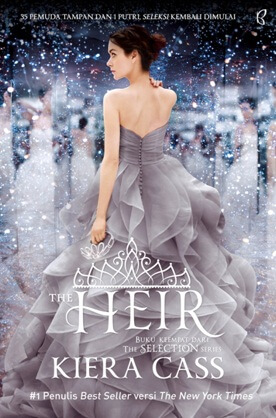Rp 15,000
Deskripsi
Delapan puluh tahun sudah Kahlen menjalani kehidupan sebagai peri laut. Tinggal dua puluh tahun lagi pengabdiannya kepada Samudra, sebelum ia bisa kembali menjadi manusia. Kahlen tak pernah melanggar aturan Samudra sampai ia bertemu Akinli, pemuda yang selama ini ada di impian Kahlen.
Manusia tampan itu membius Kahlen. Tiap bersama Akinli, Kahlen yang hampir lupa rasanya menjadi manusia, kembali berdebar-debar, layaknya gadis yang bertemu dengan cinta pertamanya. Sayangnya, jatuh cinta kepada manusia jelas pelanggaran berat. Kahlen tahu ini nggak akan mudah. Masa depan Kahlen dan nyawa Akinli terancam. Namun, maukah Kahlen menyerah?
Spesifikasi
| SKU | : | BE-525 |
| ISBN | : | 9786024304683 |
| Berat | : | 290 gram |
| Dimensi (P/L/T) | : | 14 cm/ 20 cm/ 2 cm |
| Halaman | : | 292 |
| Tahun Terbit | : | 2019 |
| Jenis Cover | : | Soft Cover |
Ulasan
Belum ada ulasan
Kamu Mungkin Suka
Lihat Semua

Dee Lestari
Tanpa Rencana (Softcover)
Rp 101,150
15%
Rp 119,000

Dee Lestari
Rapijali #2
Rp 118,150
15%
Rp 139,000

Dee Lestari
Rectoverso 2024
Rp 92,650
15%
Rp 109,000

Dee Lestari
Supernova 1: Kesatria, Putri, Dan Bintang Jatuh Republish 1
Rp 84,150
15%
Rp 99,000

Zoulfa Katouh
As Long As The Lemon Trees Grow (Republish 2025)
Rp 130,900
15%
Rp 154,000

James Dashner
Crank Palace
Rp 54,400
15%
Rp 64,000

Rick Riordan
Camp Jupiter Classified: A Probatio’s Journal
Rp 45,900
15%
Rp 54,000

Iksaka Banu & Kurnia Effendi
Pangeran Dari Timur (Republish)
Rp 160,650
15%
Rp 189,000

Dee Lestari
Rapijali
Rp 84,150
15%
Rp 99,000
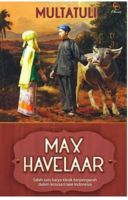
Multatuli
Max Havelaar
Rp 84,150
15%
Rp 99,000
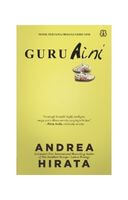
Andrea Hirata
Guru Aini
Rp 84,150
15%
Rp 99,000
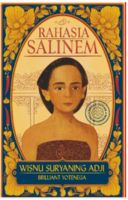
Wisnu Suryaning Ad
Rahasia Salinem
Rp 92,650
15%
Rp 109,000