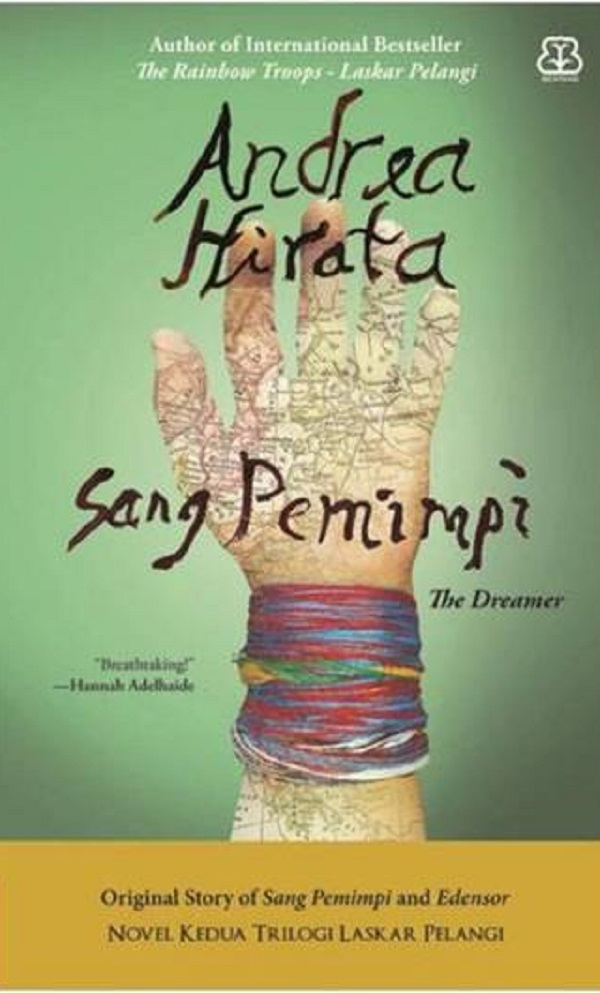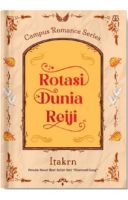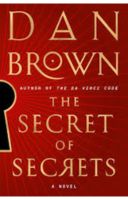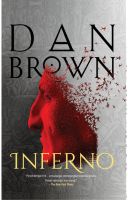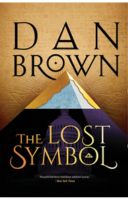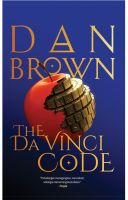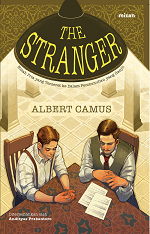
Deskripsi
Meursault, seorang Prancis yang tinggal di Aljazair, menerima telegram tentang kematian ibunya di wisma lansia di luar kota. Dia menghadiri pemakaman ibunya, tetapi tanpa tangisan dan kesedihan.
Beberapa hari kemudian, dia menembak seorang pria Arab di pantai tanpa alasan yang jelas. Meursault ditangkap dan diadili. Dia dijatuhi hukuman mati, tidak hanya karena membunuh pria Arab, tetapi juga atas kegagalannya menunjukkan kesedihan di pemakaman ibunya.
Melalui kisah Meursault, Camus mengeksplorasi apa yang disebutnya ketelanjangan manusia ketika dihadapkan pada yang absurd. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia dan dianggap sebagai salah satu maha karya sastra abad ke-20. Novel ini menempati peringkat ke-1 dalam 100 buku paling berkesan abad ke-20 versi Le Monde.
BAGIAN KESATU
I
Hari ini Ibu meninggal. Atau mungkin kemarin, aku tak tahu. Aku menerima telegram dari wisma lansia: “Ibu meninggal. Dimakamkan besok. Turut berdukacita.” Tak ada penjelasan lebih lanjut. Mungkin Ibu meninggal kemarin.
Wisma lansia itu terletak di Marengo, delapan puluh kilometer dari Kota Alger*. Aku berencana naik bus pukul dua siang sehingga bisa tiba sore hari. Dengan demikian, aku dapat mengikuti malam perkabungan dan pulang malam berikutnya. Kuajukan cuti dua hari kepada bosku dan dengan alasan semacam itu, dia tak mungkin menolaknya. Tapi, sepertinya dia tak senang.Maka kubilang kepadanya: “Bukan salah saya.” Dia tak menjawab. Kemudian, kupikir-pikir tak perlu aku berkata seperti itu. Tapi, aku tak perlu minta maaf. Justru seharusnya dia menyampaikan belasungkawa kepadaku. Tapi, esok lusa pasti dia akan melakukannya, ketika melihatku mengenakan pakaian berkabung. Sekarang nyaris rasanya seolah Ibu belum meninggal. Tapi setelah pemakaman, kenyataan itu tak terbantahkan lagi, dan segalanya menjadi lebih resmi.
Busku berangkat pukul dua. Cuaca sangat panas. Aku makan siang di restoran Céleste, seperti biasanya. Mereka semua ikut berdukacita dan Céleste berkata, “Orang cuma punya satu ibu.” Ketika aku pergi, mereka mengantarku sampai ke pintu. Pikiranku agak tersita karena masih harus mendatangi Emmanuel untuk meminjam dasi hitam dan ban lengan. Beberapa bulan yang lalu, pamannya meninggal.
Aku berlari-lari agar tidak ketinggalan bus. Pasti karena terburu-buru, berlari-lari, ditambah perjalanan yang penuh guncangan, bau bensin, langit yang menyilaukan dan pantulan cahayanya di jalan, semua itu membuatku mengantuk. Aku tertidur hampir sepanjang perjalanan. Dan ketika terbangun, kusadari diriku menyandar di badan seorang tentara yang tersenyum kepadaku dan bertanya, apakah aku datang dari jauh. Kujawab “ya” agar tak menambah panjang pembicaraan.
Wisma lansia itu terletak dua kilometer dari desa. Aku pergi ke sana berjalan kaki. Aku ingin segera melihat Ibu. Tetapi, penjaga wisma bilang aku harus lebih dulu menemui direktur. Karena direktur sedang sibuk, aku menunggu sebentar. Selama aku menunggu, penjaga itu terus bicara, sampai akhirnya aku bisa bertemu dengan direktur: dia menerimaku di ruang kantornya. Dia seorang lelaki lanjut usia bertubuh kecil, memakai tanda penghargaan Legiun Kehormatan. Dia menatapku dengan matanya yang cemerlang. Lantas dia menjabat tanganku begitu lama sehingga aku tak yakin bisa melepaskan tangannya. Dia memeriksa sebuah berkas, dan berkata, “Nyonya Meursault masuk wisma ini tiga tahun yang lalu. Anda adalah satu-satunya penanggung biaya hidupnya.” Kukira dia akan menyalahkanku karena suatu hal, sehingga aku mulai berusaha menjelaskan. Namun, dia memotong, “Tak ada yang perlu dijelaskan, Nak. Saya telah membaca berkas ibu Anda. Anda tidak mampu menyediakan apa yang dia butuhkan. Dia butuh orang yang dapat merawatnya. Pendapatan Anda pas-pasan. Lagi pula, dia lebih bahagia di sini.” Aku berkata,“Ya, Pak Direktur.”
Dia menambahkan, “Perlu Anda tahu, di sini dia punya banyak teman, orang-orang seumuran dengannya. Dia bisa berbincang dengan mereka tentang berbagai hal tempo dulu. Anda masih muda, dan pasti dia bosan bersama Anda.”
Itu benar. Dulu di rumah kami, Ibu menghabiskan waktu memandangi segala gerak-gerikku dengan membisu. Pada hari-hari pertamanya di wisma lansia, Ibu sering menangis. Tapi itu cuma karena dia belum terbiasa. Setelah beberapa bulan, Ibu pasti menangis jika dipindahkan dari wisma ini. Semuanya hanya masalah kebiasaan. Itu juga sebagian alasanku mengapa dalam tahun terakhir ini, sangat jarang aku mengunjunginya di sini. Apalagi perjalanan ke sini menyita hari Mingguku—belum lagi aku harus bersusah payah naik bus, beli karcis, dan menghabiskan dua jam untuk perjalanan kemari.
Direktur terus mengajakku bicara. Tapi aku nyaris sama sekali tak menyimaknya. Akhirnya dia berkata, “Saya rasa Anda ingin melihat ibuAnda.” Aku pun berdiri tanpa berkata-kata dan dia berjalan lebih dulu ke pintu. Di tangga dia menjelaskan, “Kami telah menyemayamkan jenazah beliau di ruang duka kecil kami, supaya tak mengganggu perasaan penghuni lain. Tiap kali ada yang meninggal, para penghuni lain gelisah selama dua atau tiga hari. Dan itu menyulitkan kerja kami merawat mereka.” Kami melintasi sebuah halaman tempat banyak orang tua mengobrol dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka mendadak terdiam ketika kami lewat. Setelah kami berlalu, di belakang kami percakapan kembali berlanjut. Suara mereka sayup terdengar seperti riuh kicau burung parkit di kejauhan. Di pintu sebuah bangunan kecil, direktur mohon izin meninggalkanku. “Silakan, Tuan Meursault. Jika Anda butuh apa pun, saya ada di kantor. Mohon diperhatikan, pemakaman sudah ditetapkan besok pukul sepuluh pagi. Kami pertimbangkan dengan demikian Anda dapat mengikuti malam perkabungan untuk mendiang. Satu hal lagi: Rupanya ibu Anda sering mengungkapkan kepada teman-temannya keinginannya dimakamkan dengan upacara keagamaan. Saya telah mengurus semuanya. Saya hanya ingin Anda mengetahuinya.” Kuucapkan terima kasih. Meski bukan seorang ateis, sepanjang hidup Ibu tak pernah peduli soal agama.
Aku masuk. Ruangan itu sangat terang, dindingnya dilabur kapur putih dan berjendela atap. Di dalamnya terdapat sejumlah kursi dan kuda-kuda penyangga berbentuk X. Dua dari kuda-kuda itu, di tengah ruangan, menopang sebuah peti mati yang tertutup. Hanya terlihat sekrup-sekrup mengkilat yang masih terpasang longgar, mencuat di atas papan-papan cokelat kenari berbercak. Di dekat peti mati tampak seorang perawat perempuan Arab yang mengenakan baju medis putih dan kerudung berwarna cerah.
Tepat pada saat itu, di belakang punggungku si penjaga wisma datang masuk ruangan. Dia pasti habis berlari. Napasnya agak terengah-engah, “Kami sudah menutup petinya, tapi akan saya lepaskan sekrupnya supaya Anda bisa melihat jenazah.” Ketika dia beranjak mendekati peti, aku mencegahnya. Dia berkata, “Anda tidak ingin melihat Ibu?” Kujawab, “Tidak.” Dia tertegun dan aku merasa tidak enak karena menurutku tak seharusnya aku berkata seperti itu. Sesaat kemudian, dia menatapku dan bertanya, “Mengapa?” tanpa nada mencela, seolah hanya ingin tahu. Aku berkata. “Entahlah.” Dia lantas memilin kumisnya yang putih dan tanpa menatapku menyatakan, “Saya mengerti.” Matanya indah, biru cerah, kulitnya agak kemerahan. Dia mengambilkan kursi untukku, lalu dia sendiri duduk tak jauh di belakangku. Si perawat berdiri dan berjalan ke pintu keluar. Pada saat itu, si penjaga berkata kepadaku, “Dia sakit lepra.” Karena tak memahami perkataannya, kucoba perhatikan perawat itu, dan kulihat di bawah matanya terpasang perban melingkari kepalanya. Di tempat yang semestinya hidungnya menonjol, perban itu rata. Hanya terlihat warna putih perban yang menutupi wajahnya.
Setelah perawat itu pergi, si penjaga berkata, “Saya akan beri Anda waktu sendirian di sini.” Aku tak tahu apa yang telah kulakukan, tapi ternyata dia tak pergi dan berdiri di belakangku. Kehadirannya di belakangku membuatku tak nyaman. Cahaya indah penghujung sore memenuhi ruangan itu. Dua ekor lebah berdengung bising di balik jendela. Dan aku mulai mengantuk. Tanpa menoleh aku berkata kepada si penjaga, “Anda sudah lama bekerja di sini?”Dia segera menjawab, “Lima tahun”—seolah sejak tadi dia menunggu aku bertanya.
Setelah itu dia banyak bicara. Andai dulu ada orang bilang, dia akan berakhir sebagai penjaga wisma lansia di Marengo, dia pasti tak percaya. Usianya sekarang 64 tahun dan asalnya dari Paris. Saat itulah aku memotong, “Oh, Anda bukan orang sini?” lalu aku teringat bahwa sebelum mengantarku ke kantor direktur, dia sempat berbicara tentang Ibu. Dia bilang Ibu harus dimakamkan secepatnya, karena iklim dataran rendah amat panas, terutama di daerah ini. Saat itulah dia memberi tahu dirinya pernah tinggal di Paris dan dia sulit melupakan kota itu. Di Paris kadang jenazah bisa tidak dimakamkan sampai tiga-empat hari. Di sini kita dikejar waktu, belum lagi kita bisa menerima kenyataan, sudah harus berlari-lari di belakang peti mati. Istrinya menegur, “Hentikan, tak pantas bicara seperti itu di depan Tuan ini.” Muka lelaki tua itu merah padam dan dia segera minta maaf. Aku langsung memotong, “Tidak apa-apa.” Menurutku, apa yang dituturkannya itu benar dan menarik.
Di ruang duka kecil itu, dia memberitahuku bahwa ketika masuk ke wisma itu, dia tak punya uang sedikit pun. Karena merasa ?siknya masih kuat, dia minta diberi pekerjaan sebagai penjaga. Aku berkomentar bahwa pada dasarnya dia juga penghuni wisma lansia ini. Dia bilang, bukan. Sejak tadi aku heran dengan caranya menyebut: “mereka,” “orang-orang lain di sini,” dan yang lebih jarang “orang-orang tua itu,” ketika membicarakan para penghuni yang sebagian tak lebih tua daripada dirinya. Tapi, tentu saja dia tak sama dengan mereka. Dia adalah penjaga wisma, sehingga dalam batas-batas tertentu dia punya hak istimewa dan wewenang atas mereka.
….
__________
Alger: nama ibu kota Aljazair dalam bahasa Prancis. Bahasa Arab: Aljir; bahasa Inggris: Algiers.
Spesifikasi
| SKU | : | QN-132 |
| ISBN | : | 9786024413002 |
| Berat | : | 440 gram |
| Dimensi (P/L/T) | : | 13 cm/ 21 cm/ 3 cm |
| Halaman | : | 160 |
| Tahun Terbit | : | 2022 |
| Jenis Cover | : | Soft Cover |
Ulasan
Belum ada ulasan