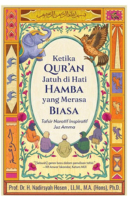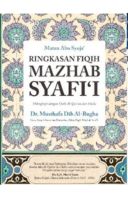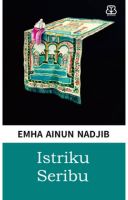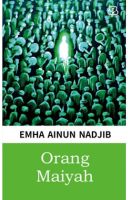The Tao Of Islam : Tuhan Dalam Pandangan Sufi (Republish)
Deskripsi
The Tao of Islam adalah sebuah antologi yang lengkap dan kaya di bidang pemikiran Islam tentang hakikat hubungan antara Tuhan dan alam semesta, alam semesta dan manusia, serta manusia dan Tuhan. Dengan memusatkan perhatian pada simbolisme gender, Sachiko Murata—seorang Muslimah Jepang yang kini menjabat sebagai Profesor Studi-Studi Agama di State University of New York, Stony Brook—memperlihatkan bahwa para pemikir Muslim klasik sering kali menganalisis realitas ketuhanan dan kaitannya dengan kosmos dan manusia melalui prinsip-prinsip polaritas atau komplementaritas, yang sangat mirip dengan gagasan filsafat Cina tentang yin/yang.
Murata yakin bahwa kesatuan pemikiran Islam dapat ditemukan pada pemahaman tentang jenis-jenis hubungan yang ada dalam realitas. Dia memberi perhatian khusus pada pandangan berbagai tokoh yang dikenal sebagai kelompok “sufi” dan “filsuf”, karena pendekatan mereka terhadap topik-topik ini memiliki keluwesan dan kehalusan yang tidak ditemukan dalam kelompok pemikir lain. Dalam buku ini, kita dapat menemukan ratusan kutipan dari karya klasik pemikir Muslim penting seperti Ikhwan Al-Shafa, Ibn Sina, dan Ibn Arabi, yang banyak di antaranya baru pertama kali diterjemahkan di sini.
SEKAPUR SIRIH
Ratna Megawangi
Tulisan Dr. Sachiko Murata telah memberikan bantuan berharga kepada saya dalam menyusun kepingan-kepingan puzzle dari gambaran berbagai fenomena. Saya sebutkan berbagai fenomena karena memang buku ini menyajikan banyak hal—seperti kosmologi, seni, agama, ?lsafat, etika, termasuk hubungan gender—yang semuanya disusun menjadi suatu rangkaian kesatuan yang mengagumkan. Maka, banyak sekali aspek yang dapat dikomentari mengenai buku ini. Namun, ada beberapa hal yang ingin saya tonjolkan, terutama mengenai hubungan gender yang isunya semakin hangat akhir-akhir ini.
Pendekatan yang dipakai oleh Dr. Murata untuk menjelaskan hubungan gender ialah dengan memakai perspektif kosmologi Islam. Pendekatan ini bisa dianggap kurang lazim, atau relatif belum dikenal oleh kebanyakan pembaca di Indonesia. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu tentang posisi di mana buku ini dapat ditempatkan dalam konteks perkembangan pemikiran feminisme.Bagi mereka yang mengikuti secara saksama arah perkembangan pemikiran feminisme sampai masa kini, tentunya akan merasakan relevansi dan keunggulan dari buku ini.
Pada penghujung abad ke-20 ini, telah terjadi perubahan paradigma berpikir dalam melihat pola hubungan gender. Antara tahun 1960 dan 1970-an, gerakan feminisme di Barat banyak dipengaruhi oleh ?lsafat eksistensialisme yang dikembangkan terutama oleh seorang ?lsuf Prancis abad ke20, JeanPaul Sartre. Sartre percaya bahwa manusia tidak mempunyai sifat alami, ?trah, atau esensi (innate nature). Eksistensi manusia bergantung pada bagaimana ia menciptakan esensinya sendiri. Karenanya, apa yang disebut esensi manusia pada dasarnya adalah socially created, yaitu tergantung dari lingkungan di mana ia berada. Pemahaman ini diterapkan oleh Simone de Beauvoir untuk menolak eksistensi sifat alami wanita dan pria. Dalam bukunya, The Second Sex (1949), Simone de Beauvoir mengatakan bahwa perempuan secara kultural diperlakukan sebagai makhluk sekunder (secondary creation) yang tugasnya mengasuh keluarga dan anaknya, serta memelihara lingkungan hidup. Dia percaya bahwa peran tersebut bukan karena sifat alamiah perempuan. Norma-norma feminin yang melekat pada wanita, seperti pengasuh, pemelihara, pasif dan penerima, adalah sifat yang dikulturkan oleh sistem patriarki. Menurut pemahaman ini, kulturalisasi norma feminin dilanggengkan oleh sistem ini agar perempuan dapat terus “ditindas”. Beauvoir menekankan bahwa para perempuan harus melepaskan diri dari norma-norma tersebut agar mereka dapat menentukan eksistensinya sendiri.
Usaha untuk memerdekakan diri ini dapat dilakukan dengan mengubah sifat pada tingkat individu, yaitu dengan menerapkan konsep pendidikan androgini. Pendidikan androgini bertujuan menghilangkan perbedaan stereotipe gender antara pria dan perempuan yang dilakukan terutama pada anak-anak usia dini. Misalnya, memberikan mainan pistol-pistolan kepada anak perempuan, dan boneka kepada anak laki-laki. Sementara itu, sebagian besar feminis percaya bahwa menghilangkan stereotipe gender pada tingkat individu adalah tidak cukup kalau tidak didukung oleh perubahan struktur masyarakat. Feminisme marxisme, sosialis, dan radikal, misalnya, menginginkan perombakan segala sistem patriarki/hierarkis dalam segi kehidupan sosial, kultural, dan politis. Cikal bakal sistem patriarkis dianggap berasal dari keluarga yang menempatkan perempuan pada posisi domestik dan pengasuhan. Maka, pembebasan perempuan dari peran domestik harus dilakukan agar dapat menunjang terciptanya masyarakat tanpa kelas. Bahkan, keluarga konvensional kalau perlu dimusnahkan karena dianggap melestarikan hierarkisme. Feminisme liberal lebih bergerak dalam usaha mengubah undang-undang dan hukum agama yang dianggap merugikan perempuan. Misalnya, penggugatan undang-undang yang mengatakan suami sebagai kepala keluarga.
Dengan demikian, gerakan feminisme Barat pada periode 1960 dan 1970-an diwarnai oleh tuntutan kebebasan dan persamaan hak agar para perempuan dapat menyamai pria dalam bidang sosial, ekonomi, dan kekuasaan politik. Kini, semakin banyak para perempuan yang telah masuk ke dunia maskulin dan berkiprah bersama-sama dengan pria. Di balik keberhasilan ini, banyak yang mengatakan bahwa para perempuan bukan saja telah memasuki dunia maskulin, melainkan juga mengadopsi nilai-nilai maskulin yang dikritiknya, serta meninggalkan sikap kepedulian terhadap pengasuhan dan pemeliharaan.1 Banyak perempuan yang telah menjadi male clone (tiruan pria) di peradaban modern Barat, yaitu peradaban ekonomi pasar berdasarkan untung-rugi, kompetisi, kekuasaan, materi, dan eksploitasi. Sumber daya uang, status, dan kekuasaan yang terbatas harus diperebutkan karena kesuksesan di dunia maskulin diukur oleh ini semua.
Peradaban manusia modern (baik pria maupun wanita) semakin terlihat ingin menguasai, mendominasi, dan mengeksploitasi. Kerusakan alam, polusi, perkosaan terhadap bumi, kriminalitas, dan menurunnya solidaritas sosial merupakan sebagian kecil contoh yang terjadi akhir-akhir ini. Lambat laun banyak feminis yang semakin sadar bahwa peradaban modern telah begitu tidak seimbang; terlalu berat pada kualitas maskulin dan kurang pada kualitas feminin, seperti cinta, kepedulian, pengasuhan, dan pemeliharaan. Timbullah pemikiran baru untuk mengoreksi kecenderungan ini. Maka, paradigma feminisme tahun 1980-an telah berbalik, yaitu memuji keunggulan kualitas feminin serta mengekstremkan perbedaan alami antara pria dan perempuan; bahwa secara esensial memang pria dan perempuan berbeda.2 Kalau sebelumnya kualitas feminin dianggap “inferior”, sekarang bahkan dianggap “superior”, para feminis tersebut mengajak para perempuan untuk melestarikan kualitas feminin agar dunia ini menjadi lebih seimbang dan segala kerusakan yang terjadi dapat dikurangi.
Teori feminisme yang menonjolkan keunggulan kualitas feminin itu disebut ecofeminism.3 Teori ini dipengaruhi oleh ?lsafat yang berkembang pesat di Barat akhir-akhir ini, yaitu ecophilosophy atau ecosophy. Ecosophy mengkritik peradaban Barat yang telah melampaui kapasitas dukung bumi. Filsafat ini banyak dipengaruhi oleh spiritualitas ketimuran dan agama-agama mistik, serta pola kehidupan orang-orang terdahulu yang selaras dengan alam. Namun, teori ecofeminism secara berlebih-lebihan mengagungkan kualitas feminin dan menganggap kualitas maskulin selalu dalam artian negatif.4
Menurut ecofeminism, alam yang disebut bumi pertiwi (Mother Nature) adalah sumber dari segala sesuatu. Berbeda dari ?lsafat eksistensialisme, ecofeminism menganggap manusia mempunyai esensi abadi, yaitu kesadaran (consciousness). Kesadaran ini adalah bagian integral dari alam, di mana esensi keseluruhannya adalah satu. Namun, peradaban modern dikatakan telah memisahkan kesadaran manusia dari alam, sehingga segala sesuatunya menjadi terfragmentasi, terpisah, teratomisasi. Manusia melihat manusia lainnya sebagai ego-ego yang saling berkompetisi. Manusia dan alam menjadi begitu terisolasi, yaitu menjadi subjek dan objek. Maka, terjadilah penguasaan dan eksploitasi alam oleh manusia.
Diferensiasi atau fragmentasi dari segala sesuatu, baik dalam diri manusia (ruh dan raga), manusia dan manusia, maupun manusia dan alam, menurut ?lsafat ecofeminism disebabkan manusia telah begitu memuja “Tuhan Maskulin” (the Father God) dan kurang memuja “Tuhan Feminin” (the Mother God). Akibatnya, manusia mengidenti?kasikan dirinya dengan the Father God sebagai yang kuasa, aktif, terpisah, independen, jauh, dan dominan.5 Pemujaan terhadap “Tuhan Feminin” menurut ?lsafat ini bertujuan merealisasikan eksistensi asal segala sesuatu, yaitu ibu, bumi, kosmos, Mother Nature, the Mother God. Penyembahan ini dapat membuat manusia mengidenti?kasikan dirinya sebagai yang dekat, kasih, penerima, pemelihara, pasif, berserah diri, dan segala kualitas feminin lainnya. Kualitas-kualitas feminin ini akan menjadikan manusia sadar bahwa elemen-elemen dalam diri manusia, antarmanusia, bumi, langit, seluruh kosmos, pada esensinya adalah satu yang berasal dari the Mother God.
Uraian di atas menunjukkan pula bahwa perkembangan teori feminisme yang terjadi akhir-akhir ini di Barat sudah menyentuh aspek-aspek spiritual. Namun, ecofeminism bagi saya belum menjelaskan beberapa problem mendasar secara tuntas, walaupun ada beberapa hal yang menarik dari ?lsafat ini. Problem yang masih membingungkan saya dari ecofeminism terutama bersumber dari latar belakang saya sebagai penganut Islam yang menempatkan tauhîd (Keesaan Tuhan) sebagai suatu yang fundamental. Ecofeminism mengakui adanya Tuhan, tetapi ada dikotomi yang terpisah antara Tuhan yang mempunyai sifat maskulin dan Tuhan yang mempunyai sifat feminin. Bagaimana ada dualisme kualitas Tuhan ini? Bagaimana hubungan keduanya? Kalau akhir dari segalanya menurut ecofeminism adalah satu, bagaimana kesatuan antara kedua kualitas Tuhan tersebut? Pada tataran sosial, ecofeminism memberi nilai yang lebih tinggi pada kualitas feminin, bahkan secara berlebihan memujanya dan mengkritik kualitas maskulin yang dianggapnya hierarkis. Bukankah ini menciptakan pola hierarkis baru bahwa kualitas feminin ada di puncak kebenaran? Apakah kualitas maskulin diciptakan untuk selalu dan selamanya jelek, atau kualitas feminin selalu dan selamanya baik? Semua ini tidak dibahas dalam ecofeminism, paling tidak sejauh yang saya ketahui.
Di sinilah letak relevansi dan keunggulan buku ini, karena buku ini membidik secara tepat pokok bahasannya untuk seolah-olah “menjawab” pertanyaan-pertanyaan di atas, walaupun buku ini tidak membahas sama sekali tentang ecofeminism. Secara sistematis dan jelas, Dr. Sachiko Murata menguraikan apa makna kesatuan dan makna dualitas yang berasal dari kesatuan. Dengan menggunakan Asmâ’ al-Husnâ, pengarang membagi nama-nama Tuhan menjadi dua: nama-nama keagungan, jalâl (kualitas maskulin), dan nama-nama keindahan, jamâl (kualitas feminin). Berbeda dengan ecofeminism yang berat sebelah terhadap simbolisasi Tuhan “feminin”, buku ini menunjukkan bahwa Tuhan, melalui nama-nama-Nya, adalah keseimbangan antara yang Agung, Kuasa, dan sebagai yang Dekat, Pengasih, Penyayang, Penerima. Dari korespondensi dualitas kualitas ini, muncul pluralitas, diferensiasi, keterpisahan, yang semuanya dijelaskan secara panjang-lebar dalam proses penciptaan jagat raya sebagai makrokosmos dan manusia sebagai mikrokosmos. Dualitas ini diterangkan baik dalam tataran Ilahiah, tataran kosmos, maupun tataran manusia, yang semuanya mempunyai analoginya. Kemudian bagaimana dualitas akan menjadi kesatuan kembali. Uraian Dr. Murata menjadi semakin jelas ketika dia menguraikan makna dan tujuan dualitas yang ditampakkan melalui adanya lawan kebalikan dari segala sesuatu; langit-bumi, atas-bawah, Tuhan-manusia, raja-abdi, cahaya-gelap, baik-buruk, feminin-maskulin.
Dr. Murata kadang-kadang mengacu dualitas Taoisme yang memang menjadi latar belakang kulturnya, yakni Asia Timur. Dia melakukan ini karena ada kesamaan konsep tersebut dengan konsep Islam, yaitu nama-nama keindahan dan keagungan Tuhan. Menurutnya, kualitas yin identik dengan nama-nama keindahan (jamâl, luthf, rahmah), sedangkan kualitas yang identik dengan nama-nama keagungan (jalâl, qahr, ghadab). Selain itu, buku ini ditujukan bagi pembaca Barat yang sudah lebih mengenal konsep yin/yang ketimbang konsep Islam seperti jamâl/jalâl, atau luthf/qahr, atau rahmah/ghadab. Dr. Murata dalam penjabarannya selalu mengacu pada teks-teks sufi terutama mazhab Ibn Arabi, tetapi tak lupa mengaitkannya dengan Al-Qur’an dan hadis.
Buku ini membuktikan bahwa maskulinitas dan feminitas pada tataran manusia masing-masing mempunyai sisi positif dan negatif, yang keduanya saling melengkapi. Keseimbangan dan kesatuan yin dan yang, feminitas dan maskulinitas, jamâl dan jalâl sebagai tujuan penciptaan, selalu ditekankan di dalam buku ini. Keseimbangan ini seharusnya tercipta baik di dalam alam lahiriah maupun batiniah. Dengan kata lain, esensi tujuan hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah untuk menjadi insân kamîl, yaitu manusia yang dapat menyatukan sisi Ilahiah jamâl dan jalâl menjadi kamâl (sempurna). Untuk ini, penulis mengajak pembaca mengerti terlebih dahulu apa makna maskulin dan feminin dalam makrokosmos (penciptaan Alam) dan mikrokosmos (penciptaan Adam dan Hawa serta manusia), baik pada tataran lahiriah maupun batiniah. Penulis mengajak pembaca untuk memahami pengertian kekal dan fana, yang Nyata dan yang tidak nyata, serta yang Absolut dan relatif. Di sinilah inti kosmologi Islam yang tujuannya ialah menegaskan tauhîd (keesaan Allah).
Kualitas feminitas dan maskulinitas dalam buku ini lebih diartikan sebagai kualitas perangai, bukan lahiriah yang kasatmata. Pada intinya, kualitas maskulin adalah aktif, melimpahkan, sedangkan kualitas feminin adalah pasif, menerima dan berserah diri. Kedua kualitas ini ada dalam diri setiap manusia. Hierarki vertikal dalam diri manusia adalah raga, jiwa (nafs), dan ruh. Ruh adalah cahaya keilahian yang harus diraih oleh setiap manusia. Buku ini menyimpulkan bahwa jiwa yang menyerahkan dirinya pada yang lebih rendah (materi, dunia, sifat-sifat negatif, dan sebagainya) adalah sifat feminin yang negatif (sifat yang menerima dan menyerah, tidak mampu melawan yang rendah). Sedangkan jiwa yang menyerahkan dirinya pada yang lebih tinggi, yaitu Akal, Ruh, Tuhan, adalah sifat feminin positif (menyerah hanya pada yang lebih tinggi). Jiwa yang ingin berkuasa, mendominasi, meninggikan diri, dan mempertuhankan diri adalah sifat maskulin negatif. Sementara jiwa yang ingin mengalahkan nafsu amarah dan ingin naik mencapai nafsu muthma’innah yang damai bersama Tuhan adalah sifat maskulin positif. Jiwa yang tenang dan damai bersama Tuhan ini adalah jiwa kesatria (pria sejati) yang telah melebur dengan Ruh/Akal. Manusia ini telah menjadi Ruh aktif (maskulin positif), yang dapat mengontrol dan menguasai jiwa dan raga agar selaras dengan cahaya Ruh dan Akal.
Melalui penjabaran ini, Dr. Murata dalam beberapa wacananya menjelaskan mengapa banyak nas Al-Qur’an dan hadis seolah-olah melihat perempuan lebih rendah daripada pria. Penulis mengajak kita keluar dari tataran lahiriah dalam mengartikan nas-nas tersebut dengan mengacu pada uraian makna batin atau takwil, sebagaimana sering diuraikan oleh beberapa su? besar. Misalnya, ada beberapa nas Al-Qur’an yang mengatakan pria sederajat lebih tinggi daripada perempuan. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma‘rûf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan (derajat) kelebihan daripada istrinya (QS 2: 228). Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) ... (QS 4: 34). Banyak lagi ayat Al-Qur’an dan hadis yang mengimplikasikan hal serupa yang mencakup hukum waris, kesaksian, kualitas akal dan agama antara pria dan perempuan. Dengan mengacu pada makna batin nas-nas di atas, siapakah yang disebut “pria” sejati yang telah mentransformasikan batinnya menjadi Akal Aktif? Ialah setiap manusia yang telah memakai cahaya Ruhnya untuk memimpin bawahannya (nafsu dan raga).
Begitu pula ada anggapan bahwa sumber dari penafsiran “negatif” tentang perempuan ialah pada proses penciptaan Adam dan Hawa. Beberapa ayat Al-Qur’an dan hadis mengatakan bahwa kaum perempuan diciptakan dari dan untuk pria. Misalnya, dua ayat Al-Qur’an, Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Tuhan menciptakan pasangannya ... (QS 4: 1), dan Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya (QS 7: 189). Juga sebuah hadis, “Berilah perhatian yang baik terhadap wanita, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang iga, dan yang paling bengkok dalam tulang iga adalah yang paling atas.”6 Sebenarnya hal yang serupa juga ada pada kitab Injil, bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Bagi para feminis, semuanya itu mengimplikasikan bahwa seolah-olah perempuan adalah makhluk kedua (secondary creation) dan pria adalah makhluk utama.
Relevansi buku ini semakin terlihat kalau kita kaitkan dengan isu-isu penafsiran ?kih perempuan (?qh al-mar‘ah) yang tengah melanda Indonesia. Para feminis, yang didukung pula oleh beberapa ahli ?kih Indonesia, menyimpulkan penafsiran bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam harus ditolak. Ayat-ayat Al-Qur’an yang secara eksplisit mengatakan bahwa istri diciptakan dari diri suaminya juga harus dibantah. Dr. Murata menekankan bahwa tidak ada satu kata pun dalam nas-nas Al-Qur’an yang tidak mempunyai makna, karena semua itu berasal dari Allah Swt. Para pembaca akan menemukan bahwa dengan menafsirkan secara lebih dalam, di luar tataran lahiriah yang relatif, segala sesuatunya pasti terkait dengan penciptaan kosmos, dan pasti ada maknanya. Seluruh kosmos berasal dari Tuhan, maka Tuhan mencintai alam semesta. Langit dan bumi tadinya sebongkah utuh, kemudian bumi dipisahkan dari langit, maka langit mencintai bumi dengan curahan hujannya ke bumi. Dari diri Adam dipisahkan Hawa, maka Adam mencintai Hawa. Begitu pula Hawa akan cenderung kepada Adam, karena Adam adalah tempat dia berasal.
Inilah yang seharusnya kita ketahui agar kita mengerti makna batin dari semua nas Al-Qur’an dan hadis. Makna hadis ini dapat menjadi nilai universal kalau dikaitkan dengan yang Universal, yang Absolut. Bukan dengan pemikiran manusia yang relatif, yang bisa menjadikan universalitas menjadi pemahaman yang totaliter. Saya pribadi tidak sependapat dengan seorang feminis yang berkata bahwa siapa pun bisa menafsirkan Al-Qur’an dan hadis menurut pemikirannya masing-masing,termasuk dirinya sendiri. Saya khawatir ini akan membuat manusia menganggap agama dapat dipakai sebagai alat untuk melegitimasi agendanya, yang dapat diubah-ubah tergantung kepentingannya. Bukan sebagai tujuan hidup hakiki yang seharusnya dicapai, yaitu mencapai jiwa muthma’innah.
Dr. Murata telah menunjukkan sikap objektif terhadap apa yang dikajinya. Dia tidak menafsirkan Al-Qur’an dan hadis menurut pikirannya, tetapi dia bergantung sepenuhnya pada nas-nas yang dia pakai. Bahkan, dia menyitir nas yang mengacu pada sebuah hadis, “Barang siapa membuat tafsir menurut opininya sendiri, maka dia telah menjadi ka?r.” Bukankah penafsiran agama oleh siapa saja akan diwarnai oleh kepentingan-kepentingan implisit dari penafsirnya? Dengan begitu, nilai hakiki agama bisa hilang karena agama bisa “dipermainkan” untuk melegitimasi tujuan kepentingan kelompok tertentu. Agama bukan lagi sebagai pengontrol manusia untuk menjadikan manusia insân kâmil, melainkan sebaliknya, agama justru dikontrol oleh manusia. Manusia akan mengklaim otoritas dirinya atau mempertuhankan pendapatnya. Inilah yang dianggap oleh Marx bahwa agama hanyalah sekadar superstruktur yang tidak memiliki nilai esensi keabadian, karena dapat dimanipulasi berdasarkan kepentingan manusia.
Penulis buku ini percaya bahwa penulis-penulis yang menjadi acuannya seperti Ibn Arabi, Jalaluddin Rumi, al-Ghazali, dan lain-lain adalah para Muslim tulus, yang menempatkan Tuhan di atas segalanya. Mereka adalah Muslim yang tidak dimotivasikan oleh keinginan pribadi untuk berkuasa, atau menguasai dunia. Dr. Murata dalam wacananya berkali-kali mengulang para penulis yang menyebutkan bahwa servanthood, pengabdian, kerendahhatian, dan penyerahan diri (Islam, feminin positif) adalah kualitas yang pertama-tama harus dimiliki oleh manusia untuk mendapatkan kedudukan wakil Tuhan di bumi, yaitu wakil yang jiwanya penuh cahaya (kesatria sejati). Saya teringat Plotinus, seorang ?lsuf abad ke-3 yang berpendapat bahwa pengetahuan adalah ada equatio rei et intellectus—artinya, “pemahaman orang yang mengetahui harus bersesuaian dengan sesuatu yang ingin diketahuinya”. Selanjutnya, menurut Plotinus, “tidak akan pernah suatu jiwa mengenal Keindahan Agung, kecuali jiwa itu sendiri menjadi indah”. Seperti halnya Jalaluddin Rumi berkata, “Hanya Kebenaran yang mengetahui Kebenaran.” Dengan kata lain, hanya mereka yang hatinya sudah bersih bercahaya yang akan mengerti makna Cahaya Al-Qur’an yang tak terbatas, yang tidak dapat diraih oleh kegelapan pemikiran, nafsu, dan agenda manusia yang sangat terbatas dan fana.
Buku ini dapat dijadikan bahan renungan kita semua, agar kita dapat mengevaluasi segala motivasi pemikiran, opini, dan tindakan kita di dunia ini. Apakah ini semua karena semata-mata memenuhi keinginan ego, sehingga kita menyerah pada nafsu yang rendah (kualitas feminin negatif), atau untuk meningkatkan jiwa pada kedudukan tertinggi: al-nafs al-muthma’innah (kesatria sejati)? Bukankah ini yang diinginkan Tuhan pada seluruh umat manusia, pria dan wanita? Hai, jiwa yang muthma’innah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha lagi diridhai-Nya. Maka, masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku (QS 89: 27-30).
***
Akhir kata, kelapangan hati dan kearifan mungkin diperlukan ketika membaca buku ini. Para pembaca mungkin akan menemukan beberapa hal yang jarang sekali dikemukakan dalam teks-teks Islam konvensional. Misalnya, uraian mengenai Ruh yang kebanyakan Muslim enggan membicarakannya. Kita perlu menempatkan Dr. Murata sebagai seorang ilmuwan yang menggali sumber-sumber teks dan harus mengemukakan hasil galiannya sebagaimana adanya. Sumber-sumber yang dipakainya sangat kaya dan dapat dijadikan khazanah ilmu yang berharga. Mungkin para pembaca akan mendapatkan pengalaman yang sama dengan saya ketika membaca buku ini, bahwa ternyata banyak sekali ilmu yang kita tidak ketahui atau belum kita mengerti. Kita semua pernah mendengar kisah su? tentang seekor katak-laut yang mendatangi seekor katak-kolam di sebuah kolam kecil. Dengan bangganya, katak-kolam itu memamerkan kedalaman air tempat tinggalnya yang hanya setengah meter. Ia menyelam dan muncul kembali ke permukaan sambil bertanya dengan angkuhnya, “Apakah kamu pernah melihat air sedalam ini, dan bagaimana keadaan tempat kamu tinggal?” Katak-laut tidak dapat menjelaskan bagaimana bentuk lautan asalnya—yang tak terbatas—kepada katak-kolam. Namun, ia berkata, “Suatu saat nanti kamu akan saya bawa ke sana, dan kamu dapat berenang di dalamnya.” Saya merasa seperti seekor “katak-kolam” di hadapan “kataklaut” teksteks su? besar yang banyak disitir di dalam buku ini. Namun, janji si katak-laut untuk membawa kita ke lautan tak terbatas memberikan secercah harapan, asalkan si katak-kolam mengetahui keterbatasan “habitatnya” (pengetahuan, pemikirannya) dan berusaha mengetahui apa yang ada di luar “habitatnya”. Jalaluddin Rumi dalam Matsnawî-nya berkata,
Selalu periksa keadaan batinmu menggunakan sang Raja dari hatimu.
Tembaga tidak pernah mengetahui dirinya tembaga, sebelum ia berubah menjadi emas.
Cinta-kasihmu tidak akan mengenal Rajanya, sebelum ia menyadari ketidakberdayaannya.
Akhirnya, kebenaran sejati hanya ada pada Allah Swt.[]
___________
1 Beberapa contohnya adalah yang ditulis oleh Suzzane Gordon, Prisoners of Men’s Dreams: Striking Out of a New Feminine Future (Boston: Little, Brown and Company, 1991); Sylvia Ann Hewlett, When the Bough Breaks: The Cost of Neglecting Our Children (1992); David Elkind, Ties that Stress: The New Family Imbalance (1994).
2 Lihat beberapa literatur yang menekankan bahwa perbedaan pria dan perempuan bukan semata-mata kultural, tetapi alamiah. Lihat Jean Baker Miller, Toward a New Psychology of Women (Boston: Beacon Press, 1986); Jessica Benjamin, The Bonds of Love (New York: Pantheon, 1988); Carol Gilligan, In a Different Voice (Cambridge: Harvard University Press); Sandra Lipsitz Bem, The Lenses of Gender (New Haven: Yale University Press, 1993).
3 Kumpulan beberapa tulisan tentang ecofeminism dirangkum dalam Irene Diamond dan Gloria Leman Orenstein (ed.), Reweaving the World: The Emergence of Ecofeminism (San Francisco: Sierra Club Books, 1990).
4 Pemujaan ini sangat jelas terlihat dalam buku Jean Shinoda Bolen, Crossing to Avalon (San Francisco: HarperCollins, 1994).
5 Michael Zimmerman, “Deep Ecology and Ecofeminism”, dalam Diamond and Orenstein (ed.), ibid.
6 Hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir.
Spesifikasi
| SKU | : | UA-268 |
| ISBN | : | 9786024413040 |
| Berat | : | 340 gram |
| Dimensi (P/L/T) | : | 16 cm/ 24 cm/ 3 cm |
| Halaman | : | 292 |
| Tahun Terbit | : | 2022 |
| Jenis Cover | : | Soft Cover |
Ulasan
Belum ada ulasan